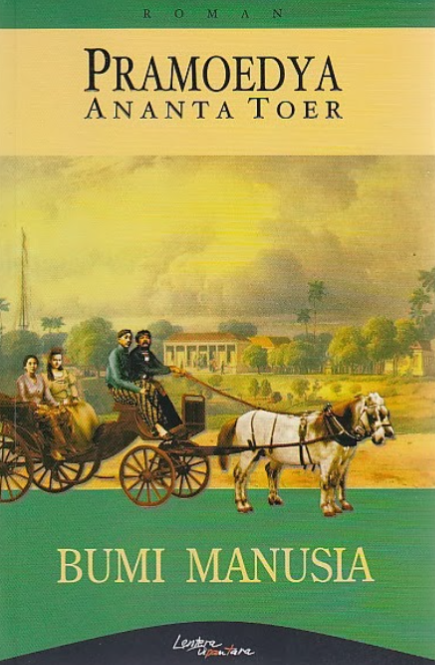
Sumber: Goodreads
Resensi Buku "Bumi Manusia"
a. Identitas buku
- Judul buku : Bumi Manusia
- Pengarang : Pramoedya Ananta Toer
- Penerbit : Lentera Dipantara
- Tahun terbit : 2011
- Jumlah halaman : 535
- Nomor ISBN : 979-97312-3-2
b. Sinopsis
Ilmu pengetahuan dan segala tentang pencariannya adalah titik lahir dari buku pertama dalam Tetralogi Pulau Buru ini. Minke, pribumi tak bernama belakang yang mengemban pendidikan setara para peranakan Eropa, adalah tokoh utama yang masa remajanya akan disoroti. Ia mengagumi rasionalitas, kemajuan, dan modernitas Eropa, segala hal yang tak dialiri pembuluh darah Bangsawan Jawanya dan nihil ditemukan di tempat kelahirannya. Maka, ia menulis, membuka suara ke dunia dalam bahasa pengeruk buminya, menatap tanah air sendiri dari ketinggian menara ilmu Barat, dan dengan buta merasa telah keluar dari kungkungan ‘pribumi’.
Akan tetapi, inilah ironi yang dijahit Pram dengan apik, kiblat keterpukauan Minke perlahan-lahan menunjukkan wajah aslinya. Pakaian, pemikiran, pergaulan, dan identitas peradabannya hanya dianggap sebagai jubah kamuflase tiruan yang tak akan pernah menjadikannya satu dari keturunan superior Eropa. Minke tak tahu bahwa keadilan hanya milik para kulit putih semata, bukan hak terjajah hina sebangsanya. Ia mulai kehilangan pegangan, dikhianati poros ilmu yang mengajaknya merdeka, namun justru menamparnya ketika mulai berani bertanya.
c. Analisis
Mengangkat tema masa penjajahan dengan latar sosio-politik, buku ini menuntun pembaca untuk membuka mata terhadap celanya penjajahan dan mengagumkannya kemajuan. Pribumi, entitas hina masa itu, harus mengejar dan mengemis sepotong ilmu dari para penjajahnya untuk setidaknya dapat dianggap terdidik. Kesaksian akan perlawanan dan amarah kekecewaan pun dituangkan cantik dengan alur maju bertulang belakang diksi puitis. Ini diperkuat dengan sudut pandang orang pertama yang mendudukan kita sebagai pejuang kebebasan itu sendiri dengan seluruh suka dan duka yang menyertai.
Penokohan dalam cerita ini turut serta memperluas pandang terhadap warna-warna lapisan sosial serta borgol-borgol individual yang mengekang mereka masa itu sebab nihilnya pengakuan terhadap hak dasar manusia. Namun, di balik latar belakang karakter mereka, disuguhkan pula daya pikat pribadi yang membuat kisah dan pembawaan tiap-tiap perkenalan membekas dan memberikan pemahaman baru. Gundik berpendidikan, gadis cantik tanpa pengakuan, peranakan Eropa penuh kedengkian, serta banyak lagi paradoks kompleks yang mengokohkan impresi para nama-nama di buku ini.
d. Kelebihan dan Kekurangan
Satu hal menonjol yang menjadi kelebihan dari buku ini ialah bagaimana Pram mengisahkan penjajahan dari sudut pandang tokoh terpelajar. Meski ini mengurangi esensi penderitaan yang dialami pribumi, perspektif Minke menyuguhkan cerita lebih memikat karena ia dapat secara subjektif menyaring dan menimbang kelebihan bangsa kaum putih mana yang akan ia tiru. Guratan ketidaksukaannya terhadap para leluhur dan peninggalannya yang ia anggap kolot juga turut menyadarkan pembaca bahwa masa pra-penjajahan tak jauh lebih baik.
Monolog Minke juga merupakan poin kuat yang menjadikan buku ini begitu menghipnotis. Pembaca secara reflektif dan filosofis diperkenalkan ke tokoh utama melalui renungan-renungan akan peristiwa yang menimpanya. Pemikiran-pemikirannya, pertanyaan tak terjawabnya, hingga batin penuh pemberontakannya membuat ia menjadi tokoh yang tidak semata hitam dan putih. Ini secara tidak langsung menjadi paragraf-paragraf justifikasi dan penjelasan akan aksi yang akan ia lakukan, mengajak kita untuk melihat dunia dari kacamatanya dan menyetujui apa-apa yang diperbuatnya.
Lalu, tak bisa diabaikan pula cara Pram merepresentasikan perempuan sebagai pejuang seperti Nyai Ontosoroh. Dalam dunia yang maskulin dan kolonial, Nyai justru dominan dalam pergaulan yang memandangnya hina, ia paham baca tulis, piawai dalam dialog kritis, serta teguh akan ketidaksukaannya terhadap seksisme sistematis. Ia adalah kekuatan diam yang membentuk kembali makna martabat dan pendidikan di tengah keterbatasan status sosialnya. Bahwa Pram menulis perempuan sedemikian kuat di masa ketika gagasan emansipasi belum menjadi arus utama, menjadi alasan mengapa buku ini melampaui zamannya.
Akan tetapi, hal yang terasa mengganjal selama membaca ialah bagaimana konflik utama dalam Bumi Manusia terlalu terserap dalam hubungan percintaan antara Minke dan Annelies. Memang, kisah mereka menyentuh dan penuh tragedi, namun porsi yang begitu besar pada romansa ini justru membuat potensi besar tokoh Minke sebagai kaum terdidik pribumi kurang tergali maksimal. Alih-alih mengelaborasikan bagaimana ilmu dan pemikiran Minke bisa menantang struktur kolonial, pembaca malah lebih sering disuguhi gundah gulana terhadap cinta remaja yang fana.
Alur cerita yang dibangun pun cenderung lambat dan berputar-putar. Pram memang gemar memberi ruang bagi tokoh-tokohnya untuk berbicara panjang dan merenung, tetapi ritme seperti ini kadang membuat pembaca kehilangan ketertarikan untuk mengikuti konflik sampai akhir. Beberapa bagian terasa seperti jeda panjang sebagai pengisi lembar kosong sebelum sesuatu yang penting benar-benar terjadi. Ketika suasana hati tokoh lebih sering ditampilkan daripada perkembangan peristiwa, pembaca bisa merasa tenggelam dalam narasi yang pekat dan terperangkap tanpa arah yang pasti.
Lalu, satu kelemahan yang terasa menonjol secara ideologis adalah minimnya sorotan terhadap penderitaan kaum pribumi dari lapisan masyarakat paling rentan. Latar belakang Minke sebagai anak priyayi yang berpendidikan membuatnya memiliki jarak sosial yang nyata dengan realitas mayoritas masyarakat. Meskipun ia menunjukkan kemarahan terhadap ketidakadilan kolonial, responsnya sering kali muncul dari posisi yang relatif aman. Akibatnya, penderitaan yang tergambar dalam novel ini lebih banyak berasal dari kegelisahan moral dan batin kelas menengah terdidik, bukan dari luka struktural yang dialami oleh mereka yang paling keras ditekan oleh sistem.
e. Penilaian Penulis
Bumi Manusia merupakan kodifikasi elok yang memperkawinkan pergulatan lapisan kelas sosial dengan realitas kekacauan atmosphere pemerintahan yang membatasi ruang gerak para tokoh. Dengan fokus untuk memperkenalkan kondisi akhir abad-19, Pram berhasil menarik pembaca untuk terjun ke dunia antik dimana teknologi merupakan komoditas langka yang hanya diketahui namanya. Pengkisahan bagaimana pengetahuan dan keingintahuan adalah tulang punggung peradaban, turut serta membungkus rapi hasrat tokoh utama dalam mengejar kemajuan penjajahnya.
Warna-warna romansa dari percintaan Minke juga memberikan karakter unik dari kisah ini, dimana ketegangan latar cerita dipadukan manis dengan kegirangan ingin bertemu sang kekasih. Bahkan perkenalan polos dua remaja ini menjadi benang merah dari kejadian yang mendorong pendewasaan penting mereka yang terlibat. Sisip-sisipan ini lah yang menjadi jeda dari polemik yang dihadapi Minke sehingga menjadikan buku ini tidak terlalu padat akan kegundahan revolusioner, namun juga menyoroti sisi realistis keremajaan tokohnya.
Pun kepiawaian Pram dalam menghantarkan pesan ideologis dari tiap kutipan perbincangan menjadi faktor yang menjadikan buku ini begitu mengagumkan. Pertanyaan filosofis tiap monolog dan dialognya memaksa pembaca untuk turut serta menghayati kegelisahan dan kegelisahan mereka. Kekaguman yang juga merupakan emosi kuat dalam buku ini tak kurang mendapatkan penyampaian yang sama menyadarkannya, dengan simbolisme kuat yang sepadan. Kurang-lebih, kebahasaan yang bertugas sebagai penghantar perasaan pahit manis dalam buku ini hanya dapat dideskripsikan dalam kata “sukses.”
f. Kesimpulan dan Rekomendasi
Dalam lingkup menyeluruh, Buku Bumi Manusia merupakan buku yang cocok untuk dinikmati bagi para pembaca yang ingin terjun ke genre sejarah, namun enggan karena khawatir terlalu berat. Karena dalam buku fiksi ini, dipadukan fakta historis dengan pembawaan unik yang mengisahkan penjajahan dari teropong yang lebih mudah dicerna. Kompleksitas para tokohnya yang berakar kuat dari latar belakang sosial mereka juga menawarkan refleksi realitas terhadap betapa terpuruknya masa itu.
Maka penulis sangat merekomendasikan buku ini untuk para pemuda hingga orang dewasa tanpa batasan batasan usia yang ingin mengulik bagaimana situasi masa lalu ketika bangsa kita masih hanya bagian dari Hindia-Belanda. Karena sejarah yang dibungkus dalam fiksi, adalah penghantar tak kalah baik untuk kesadaran perjuangan berabad-abad para tokoh yang berani melawan.
Penulis: Fairuz Fakhirah
Baca Artikel Menarik Lainnya!

Skema Impor Minyak Satu Pintu Pertamina Pada 2025:...
08 October 2025
Waktu Baca: 5 menit
Baca Selengkapnya →
Ganti Rugi Keracunan Makanan Bergizi Gratis: Siapa...
04 July 2025
Waktu Baca: 4 menit
Baca Selengkapnya →
Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut Memanas, Prabowo Siap...
15 June 2025
Waktu Baca: 2 menit
Baca Selengkapnya →